Pagi itu, langit masih sedikit mengantuk. Embun di ujung daun belum mau pergi,
dan aroma kopi hangat sudah menguar dari dapur kecil di sudut rumah.
Dari
balik jendela kamarnya, Rani duduk bersila sambil menggenggam mug
kesayangannya yang berisi kopi robusta panas dengan sedikit gula. Ia memperhatikan sekawanan burung kecil
yang hinggap di pagar depan rumahnya.
“Burung gereja,” gumamnya
pelan.
Burung-burung kecil itu tampak santai, mematuk-matuk remah roti yang mungkin tertinggal sejak sore kemarin. Tubuhnya mungil, warna bulunya campuran cokelat dengan putih keabu-abuan, dan kepalanya merah bata seperti tanah liat yang dipanaskan matahari. Lucu juga, pikir Rani.
“Aku dulu
kira burung gereja itu burung lokal,” katanya, masih mengamati dari
jendela.
Padahal kenyataannya, si Passer montanus ini bukan
asli Indonesia. Ia datang dari daratan Asia dan entah bagaimana—mungkin karena
petualangannya yang panjang—ia akhirnya menemukan rumah baru di negeri ini.
Kini, burung ini bisa ditemukan di mana-mana: dari Sumatera, Jawa, Bali,
sampai Kalimantan. Bahkan di gang-gang kota dan pinggir sawah pun ia eksis.
Yang menarik, di berbagai daerah Indonesia, orang menyebutnya beda-beda. Ada yang
bilang burung pipit, ada juga yang menyebutnya pingai. Tapi yang paling
populer tentu saja: burung gereja.
“Katanya sih, dulu mereka suka
bersarang di atap gereja,” Rani membatin sambil tersenyum. “Pantas aja dapet
nama itu.”
Ia memperhatikan gerakan si burung kecil. Terbangnya
rendah, bergerombol dengan teman-temannya. Mereka tampak nyaman di antara
manusia—tidak seperti burung-burung lain yang lebih suka menjaga jarak.
Burung gereja itu memang terkenal adaptif. Mau tinggal di gedung tua, pasar, taman
kota, bahkan di dekat tempat sampah pun oke-oke saja. Mereka juga suka
membangun sarang di sela-sela bangunan, kadang di langit-langit, atau lubang
pohon. Tidak terlalu rewel.
“Kadang kita nganggep mereka remeh,”
kata Rani sambil menyeruput kopinya. “Padahal mereka punya peran penting juga
lho. Mereka makan serangga, jadi bisa bantu ngontrol hama. Dan kadang mereka
juga bantu nyebarin biji-bijian.”
Ia teringat cerita seorang petani
di desa neneknya yang sering mengeluh tentang burung gereja yang doyan bulir
padi. "Ah, dasar pipit, hama kecil!" begitu katanya waktu itu. Tapi sekarang
Rani paham—kadang yang kita anggap pengganggu, justru bagian penting dari
siklus alam.
Burung-burung kecil itu masih di sana. Mungkin mereka satu keluarga. Atau satu koloni, karena burung gereja
memang suka hidup berkelompok.
Yang betina biasanya sedikit lebih
pucat warnanya, tapi tetap mirip. Saat musim kawin, yang jantan akan mulai
berkicau lebih nyaring—semacam usaha menarik perhatian. Sekali bertelur,
mereka bisa menghasilkan lima sampai enam butir. Lucunya, kedua induk akan
bergantian mengerami dan merawat anak-anaknya sampai mandiri.
“Jadi,
burung ini bisa poligami juga ya,” Rani terkekeh. “Sungguh kehidupan cinta
yang sibuk.”
Usia hidup mereka juga nggak lama, rata-rata tiga tahun. Tapi selama itu, mereka sudah berkontribusi banyak—tanpa kita sadari.
Dan mungkin itu cukup.
Burung-burung itu akhirnya terbang pergi,
meninggalkan pagar kosong yang tadi sempat jadi panggung kecil mereka. Rani
menghela napas, lalu menulis satu kalimat di journal hariannya:
Yang terlihat biasa, seringkali menyimpan kisah luar biasa.
🎥 _Ingin melihat lebih dekat
kehidupan burung gereja? Cek video yang diunggah oleh pemilik channel RHD Kicau
Official di bawah ini.
*Klik gambar produk untuk melihat detailnya:





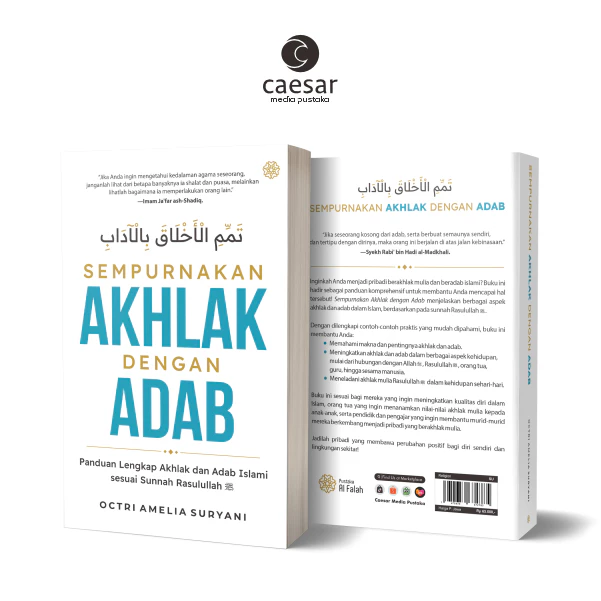
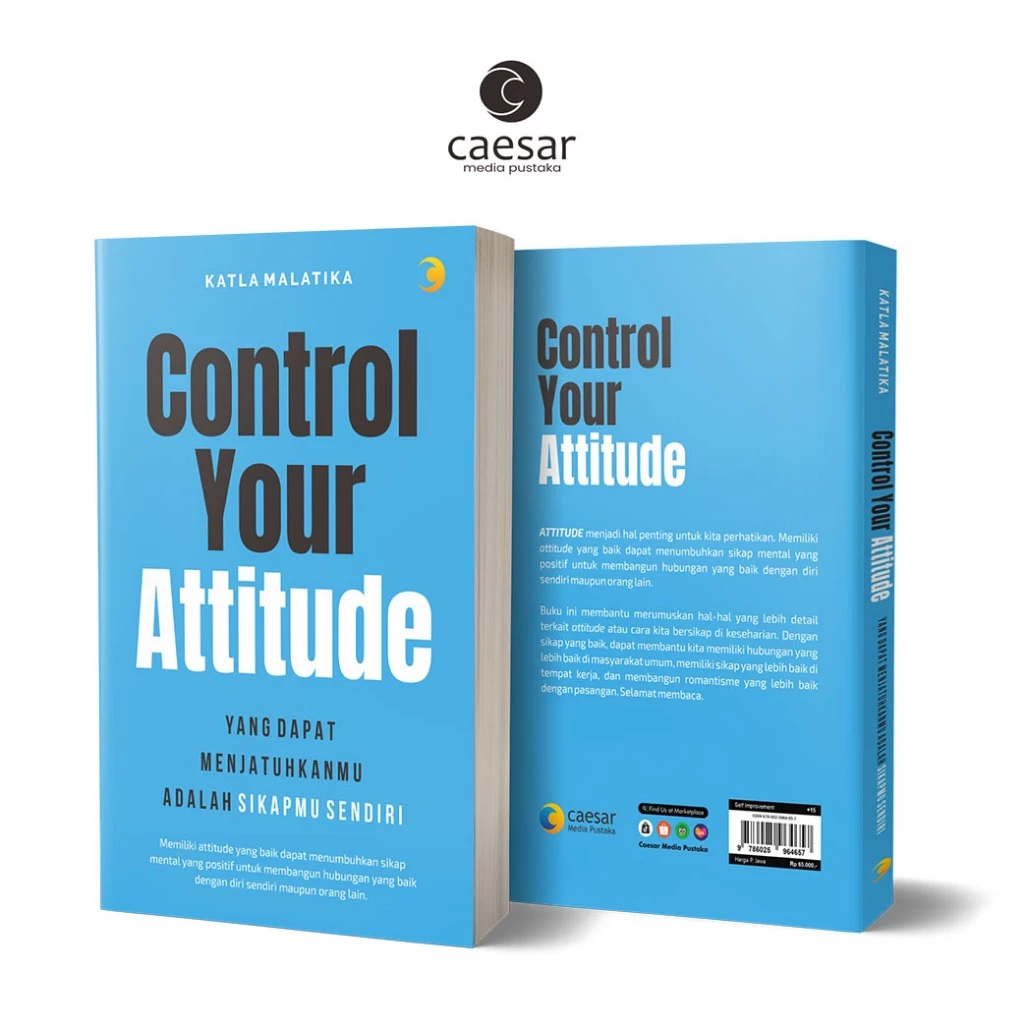

Posting Komentar
Silakan Meninggalkan Komentar